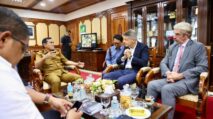Banda Aceh, Acehglobal – Hampir 20 tahun pasca-penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki pada 15 Agustus 2005, yang menandai berakhirnya konflik bersenjata selama 29 tahun antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia (RI), janji perdamaian di Aceh ternyata masih menyisakan polemik.
Halim Abe, Juru Bicara Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Kuta Pase, mengungkapkan bahwa kesepakatan damai yang seharusnya menjadi pintu masuk menuju kesejahteraan rakyat Aceh justru menjadi sumber ketegangan baru.
Dalam pernyataannya pada Selasa (6/5/2025), Halim Abe menegaskan bahwa MoU Helsinki, yang ditanda tangani oleh GAM dan RI, merupakan cara terbaik untuk mewujudkan kedaulatan hukum, politik, dan keamanan di Aceh pasca-konflik.
“Pada hakikatnya, penandatanganan nota kesepahaman itu adalah komitmen bersama untuk perdamaian yang sejati, yang akan membawa kesejahteraan bagi rakyat Aceh,” ujar Halim.
Ia menambahkan bahwa kedua pihak sepakat perdamaian hanya dapat tercapai dengan melaksanakan butir-butir kesepakatan yang telah dirumuskan di meja perundingan Helsinki. Namun, Halim menyoroti bahwa hingga kini, setelah hampir dua dekade berlalu, implementasi MoU Helsinki justru menjadi polemik yang terus berulang.
Menurutnya, penyimpangan terhadap poin-poin MoU, terutama dalam kebijakan politik, hukum, dan keamanan di Aceh, menjadi pemicu ketidakpercayaan dan membangkitkan trauma masa lalu rakyat Aceh.
“Penyimpangan ini terkesan dilakukan secara terstruktur dan sistematis oleh pemerintah pusat,” tegasnya. Ia menggunakan analogi dalam bahasa Aceh, “Watee di laot sapeu pakat, ban troh u darat laen keunira,” yang artinya apa yang disepakati di laut (Helsinki) ternyata berbeda ketika sampai di darat (implementasi di Aceh).
Halim mempertanyakan pihak mana yang sebenarnya berkhianat dalam kesepakatan ini.
Pernyataan ini sejalan dengan sentimen yang telah lama mengemuka di kalangan masyarakat Aceh, termasuk desakan dari berbagai pihak seperti Wali Nanggroe, politikus, LSM, dan organisasi HAM, yang menilai pemerintah pusat belum sepenuhnya merealisasi butir-butir MoU Helsinki.
Salah satu isu yang kerap mencuat adalah belum terbentuknya Pengadilan HAM untuk Aceh dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang memadai, sebagaimana diatur dalam MoU, untuk menangani pelanggaran HAM berat selama konflik 1976-2005.
Polemik ini juga diperparah dengan rencana penambahan empat batalyon TNI di Aceh, yang menuai penolakan keras karena dianggap melanggar MoU Helsinki.
Padahal, MoU tersebut membatasi kehadiran personel TNI organik di Aceh hanya 14.700 orang sebagai bagian dari pengaturan keamanan pasca-konflik.
Sebaliknya, pandangan berbeda disampaikan Rektor Universitas Malikussaleh, Herman Fithra, yang melihat kehadiran TNI sebagai peluang untuk optimalisasi lahan tidur dan program pembangunan nasional di Aceh.
Menurut Halim Abe, Komitmen damai bukan hanya sebatas perut dan lahan tidur, Sungguh naif mengangkat senjata kalau tujuannya hanya sebatas memperjuangkan perut seperti pola pikir Rektor dan dekan Universitas malikussaleh.